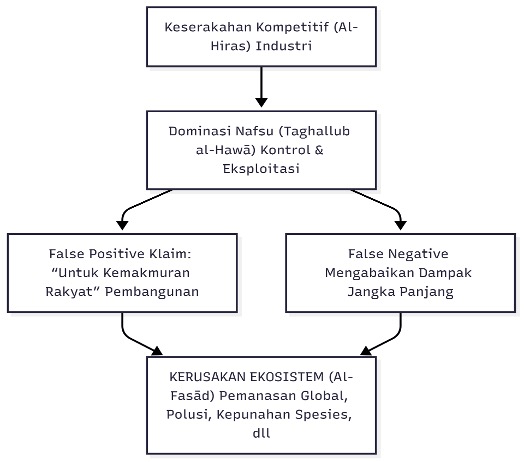Pernah baca doa Nabi Ibrahim di QS Al-Baqarah:126-129? Urutannya jenius:
1. “Ya Allah, jadikan negeri ini AMAN & MAKMUR” (Sandang-pangan dulu!)
2. “Berikan keimanan pada penduduknya” (Setelah kebutuhan dasar terpenuhi)
3. “Utuslah Rasul dari kalangan mereka” (Untuk mengajar & menyucikan)
Lihat? Kesejahteraan umum dulu, baru kesalehan pribadi. Ini bukan teori—Wali Songo buktikan di Jawa: masuk lewat budaya (wayang, seni) dan solusi kehidupan, baru ajarkan tauhid.
Tapi ini yang lebih bombastis: Doa itu dijawab Allah dengan ledakan pengetahuan!
QS 2:151 menjawab: Rasulullah ﷺ diutus bukan cuma bawa hukum, tapi “mengajarkan apa yang BELUM KALIAN KETAHUI” (wa yu’allimukum ma lam takunu ta’lamun).
Ini kontrak ilahi: Ikuti Rasul, Allah janjikan pengetahuan baru yang tak terbayangkan.
—
SEJARAH YANG DISEMBUNYIKAN: SAINS ADALAH IBADAH
Para sejarawan Barat sering “lupa” ceritakan ini: Zaman Keemasan Islam (8-14 M) adalah revolusi sains pertama dunia.
Mereka pikir: Yunani Kuno → “Abad Kegelapan” → Renaisans Eropa.
FAKTA: Ada mata rantai hilang bernama ISLAM yang bukan sekadar “jaga warisan Yunani”, tapi meledakkan inovasi.
Contoh konkret: Ibnu al-Haitsam (Alhazen).
Dari Basrah (965 M). Frustasi melihat penyakit mata merajalela di gurun Arab.
Dia eksperimen, ukur, catat — bukan percaya teori Yunani buta.
Hasilnya? Kitab al-Manazir — buku yang gulingkan 1.500 tahun teori penglihatan keliru, jadi fondasi optik modern & prinsip kamera!
Motivasinya? Mengatasi penderitaan manusia.
Baginya: mencari ilmu = ibadah = memahami ayat Allah di alam.
Ini baru SATU nama. Ada Al-Khawarizmi (Aljabar, Algoritma), Ibnu Sina (kedokteran), Al-Jazari (robotika awal) — semua produk semangat ayat “mengajarkan yang belum diketahui”.
—
PROVOKASI INTELEKTUAL: MENGAPA KITA DI SINI SEKARANG?
Pertanyaan menggelitik: Jika umat Islam dulu bisa jadi pelopor sains karena Al-Qur’an, mengapa sekarang justru tertinggal?
Jawabnya mungkin di urutan doa Ibrahim yang kita BALIK:
Kita sering fokus pada:
1. Kesalehan ritual individu
2. Peneguhan identitas kelompok
3. …lupa membangun peradaban yang aman, makmur, dan berpengetahuan
Kita ingin “khilafah” tapi lupa bahwa khilafah sejati dimulai dari membangun jalan, rumah sakit, sekolah, dan laboratorium yang maju — seperti yang dilakukan Umar bin Khattab.
—
TANTANGAN UNTUK KITA:
Allah sudah beri cetak biru (doa Ibrahim) dan kontrak janji (QS 2:151). Warisan saintis Muslim sudah buktikan: Islam kompatibel dengan puncak peradaban.
Sekarang, generasi kita yang harus menjawab:
· Apa “yang belum diketahui” yang akan kita temukan?
· Ilmu apa yang akan kita kontribusikan untuk umat manusia?
· Bagaimana kita membangun kemakmuran yang menjadi fondasi kesalehan kolektif?
Ini bukan soal nostalgia. Ini soal meneruskan estafet yang sempat terputus.
Karena menjadi rahmatan lil ‘alamin di abad 21 berarti menjawab tantangan zaman dengan ilmu, inovasi, dan kepemimpinan yang berkeadilan.
Allah sudah penuhi janji-Nya. Sekarang, giliran kita memenuhi panggilan sebagai khalifah di bumi.
Dari doa Ibrahim, lahir peradaban. Dari semangat “belum diketahui”, lahir ilmuwan Muslim. Sekarang, giliran kita menulis bab baru.
Siap mengubah pola pikir?