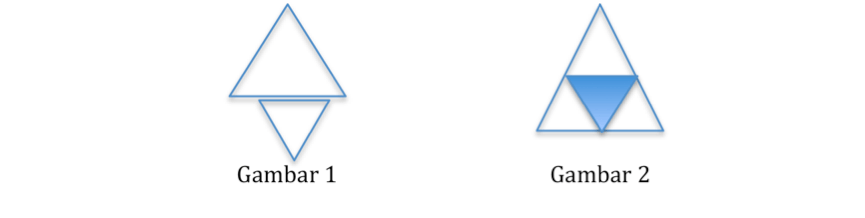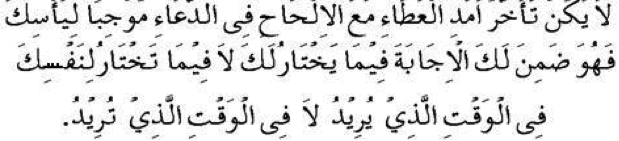Jaring dan Ikan
Uzair Suhaimi
uzairsuhaimi.wordpress.com
Sebagian besar ikan yang terjerat dalam jaring konon tidak menyadari terjerat sehingga tidak terpikir untuk membebaskan diri. Sebagian kecil ikan yang terjerat itu konon menyadari kondisinya sehingga berjuang keras untuk membebaskan diri: sebagian besar gagal, sisanya berhasil. Anggota dari kelompok ke-3 ini– yang berusaha membebaskan diri dan berhasil– relatif sangat sedikit jumlahnya. Tetapi ada kelompok ikan lain dengan jumlah anggota jauh lebih sedikit: anggota kelompok ini tidak tertarik oleh jaring sehingga sejak awal terbebas dari jeratannya. Dari uraian di atas kita dapat membagi ikan– dalam kaitannya dengan jaring– ke dalam empat kelompok: (1) mereka yang terjerat jaring tetapi “tidak menyadari” bahwa ia terjerat, (2) mereka yang “menyadari” terjerat dan berjuang keras untuk membebaskan diri, (3) mereka yang berhasil keluar dari jeratan dan bebas, dan (4) mereka yang sejak awal terbebas dari jeratan jaring.
Dalam cerita di atas yang dikemukanan oleh Ramakrishna itu[1] jaring melambangkan dunia, sedangkan ikan melambangkan jiwa manusia. Disini terlihat “kelincahan” tradisi India dalam memanfaatkan kasus pengalaman hidup sehari-hari sebagai titik tolak pemikiran filsafat; ini berbeda dengan tradisi Barat yang terlalu mengandalkan reasoning atau spekulasi intelektual sehingga Filsafat Barat oleh Swami Yasiwaranda dikritik sebagai hanya senam intelektuali yang tidak banyak bermafaat bagi kehidupan nyata sehari-hari[2]. Memberikan label filsuf kepada sosok Ramakrishna (1836-1886) mungkin tidak memadai karena beliau adalah seorang yogi dan mistis India, bergelar Bagawan dan Mahatma, dan dilaporkan sangat dihormati dan diakui kebesarannya oleh semua pemuka agama atau tradisi besar dunia termasuk Kristen (Ortodoks), Islam, Budha, dan Sikh[3].
Menggunakan analogi jaring-ikan itu Sang Bagawan membagi jivas atau jiwa-jiwa individual terbagi ke dalam empat kelas: (1) Badha (terikat, the bound), (2) Mumukshu (pencari kebebasan, the seeker after freedom), (3) Mukta (terbebas, emancipated) dan (4) Nitya-Mukta (bebas abadi, the eternally free). Seperti disinggung sebelumnya, anggota dari kelas jiwa ke-4 jumlahnya paling sedikit, mungkin setara dengan apa yang dikenal dalam kajian sufi sebagai “orang-orang khusus dari kelompok orang khusus” (khawasul-khawaas). Sebaliknya, kelompok ke-1 merupakan mayoritas sehingga memperoleh perhatian lebih dari Sang Bagawan.
Jiwa Badha
Menurut Sang Bagawan, ikan dalam kelompok pertama, ketika tertangkap, akan lari dan bersembunyi dalam lumpur dengan tetap berada dalam jeratan jaring, masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi ke dalam lumpur. Inilah gambaran orang yang berjiwa Badha. Selanjutnya Ramakrishna melukiskan mereka sebagai orang yang tidak mampu menarik pelajaran dari pengalaman hidup yang pahit seperti terungkap dalam kutipan langsung berikut[4]:
Those who are thus caught in the net of the world are the Baddha, or bound souls. No one can awaken them. They do not come to .their senses even after receiving blow upon blow of misery, sorrow, and indescribable suffering. …. The bound souls may meet with great grief and misfortune, but after a few days, they are just as they were before. The wife may die or become unchaste, the man will marry again; his son may die, he will be extremely sorrowful, but he will soon forget him. The mother of the boy may be overwhelmed with grief for a short time, but in a few days she will once more be concerned her personal appearance and will deck herself with jewels and finery.
Mereka yang terjerat dalam jaring dunia adalah Baddha, atau jiwa yang terbelenggu. Tidak ada yang bisa membangunkan mereka. Mereka tidak bergeming bahkan setelah menerima berbagai deraan penderitaan, kesedihan dan kesengsaraan yang tak terlukiskan. …. Jiwa yang terbelenggu (dunia) itu bisa saja mengalamai kesedihan dan kemalangan yang dahsyat, tapi setelah beberapa hari mereka akan kembali seperti sebelumnya. Istrinya bisa mati atau menjadi pelacur, tapi orang itu akan menikah lagi; anaknya bisa saja mati dan ia akan sangat bersedih karenanya tetapi akan segera melupakannya. Ibu dari anak itu mungkin akan mengalami kesedihan luar biasa (atas kematian anaknya) tetapi itu hanya untuk waktu singkat, dalam beberapa hari ia tidak akan peduli dan kembali lebih memperhatikan penampilan pribadi dengan segala aksesori perhiasan.
Ciri orang yang berjiwa Badha lainnya adalah standar moralnya yang rendah serta tidak memiliki apresiasi terhadap kehidupan beragama. Mengenai hal ini Ramakrishna mengungkapkan[5]:
There is another sign of a Baddha, or worldly soul. If you remove him from the world and put him in a better place, he will pine away and die. He will work like a slave to support his family, and he will not hesitate to tell lies, to deceive or to flatter in order to earn his livelihood. He looks upon those who worship God or who meditate on the Lord of the universe as insane. He never finds a time or opportunity to think of spiritual subjects. Even at the hour of death he will think and talk worldly things. Whatever thought is strongest in the minds of worldly people comes out at the time of death. If they become delirious, they rave of nothing but material objects.
Ada tanda lain dari Baddha, atau jiwa duniawi. Jika Anda memindahkan dia dari dunia dan menempatkannya di tempat yang lebih baik, ia akan merana dan mati. Dia akan bekerja seperti budak untuk mendukung keluarganya, dan ia tidak akan ragu untuk berbohong, menipu atau untuk menyanjung dalam rangka untuk memperoleh penghasilan. Dia memandang orang-orang yang menyembah Allah atau yang merenungkan Tuhan alam semesta sebagai gila. Dia tidak pernah menemukan waktu atau kesempatan untuk memikirkan pelajaran spiritual. Bahkan pada saat kematian ia akan berpikir dan berbicara mengenai hal-hal yang bersifat duniawi. Apapun yang menjadi pikiran terkuat di benak orang-orang duniawi akan terungkap pada saat kematian. Jika mereka menjadi mengigau, mereka igauannya hanya terkait dengan benda-benda material.
Sayangnya Ramakrishna yang hidup di abad ke-19 sehingga tidak sempat menyaksikan gaya hidup manusia kontemporer. Seandainya kesempatan itu ada, penulis menduga beliau akan memasukkan para elit berikut sebagai contoh kasus orang yang berjiwa Badha: penguasa negara yang berani merampok secara kasar hak-hak dasar rakyatnya, pejabat publik dengan fasilitas wah tetapi masih berani mengkorupsi uang rakyat, para pengusaha “sukses” tetapi tega mengambil hak-hak pekerja, profesional muda “sukses” yang menghabiskan hampir seluruh waktu dan energinya untuk menata karir duniawi tanpa menyisakan ruang dan waktu untuk berpikir hal-hal yang luhur.
Kebanyakan kita tampaknya tidak layak bermimpi untuk memiliki jiwa ke-4 (Nitya Mukta) tetapi patut berlindung kepada-Nya dari sifat-sifat orang berjiwa ke-1 (Badha). Kita dapat berharap minimal memilki jiwa ke-2 (Mumukshu) sambil terus berupaya dan berharap pertolongan-Nya agar diangkat ke kelas jiwa ke-3 (Mukta). Kenapa perlu pertolongan-Nya? Karena jiwa kita berada dalam genggaman-Nya seperti terungkap dalam ujung doa tahiyat akhir dalam tradisi Islam: “Wahai yang membolak-balikan jiwa, tetapkanlah jiwaku dalam agama-Mu dan ketaatan kepada-Mu (Ya muqallibal quluub, tsabbit qalbii ‘ala a diinika wa’ala thaa’atika).
Apa kata agama?
Konon semua agama berbeda dalam hal perumusan teologi tetapi mempunyai bahasa yang sama ketika terkait dengan kesalehan moral pribadi dan sosial. Hemat penulis semua agama mengajarkan hidup sederhana, menentang kemewaahan berlebihan, dan merasa prihatin dengan moralitas masyarakat yang berjiwa Badaha.
Islam, sejauh yang penulis pahami, tidak menentang secara serta merta kehidupan dunia: secara fisikal kita merupakan bagian dari dunia sehingga kehidupan dunia tak terhindarkan. Kita tidak mungkin menghindari ketertarikan kepada “harta” dan “wanita”; by design itulah sifat-dasar kita:
Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan anak-anak, harta benda yang bertumpuk berpa emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan dunia dan sisi Allahlah tempat kembali yang baik[6].
Tantangannya adalah bagaimana mengendalikan sifat-dasar kita itu sehingga keduanya tidak menguasai dan memperbudak jiwa kita. Menghadapi tantangan ini jalan Islam secara umum– ini mungkin berbeda dengan jalan Kristen atau Hindu—mengambil “jalan tengah” atau moderat. Hal ini diilustrasikan oleh kisah Usman Ibn Mazhun (adik Umar Ibn Khattab), seorang sahabat Nabi Saw yang dikenal paling zuhud, bahkan sebelum masa turunnya wahyu. Dia sangat tertekan oleh hasrat-hasrat duniawi sehingga suatu saat dia meminta izin kepada Nabi SAW untuk bertapa dan menghabiskan sisa hidupnya untuk menjadi sorang fakir. Jabawan Nabi Saw[7]:
“Tidakkah engkau jadikan aku sebagai teladan bagimu?” “Aku menikah, aku makan daging, dan aku juga berpuasa, dan aku juga berbuka. Bukan dari kaumku orang yang menjadikan dirinya dan orang lain fakir”. “Engkau berpuasa setiap hari dan asyik beribadah sepanjang malam”. “Tidak begitu, dan jangan lakukan itu karena sesungguhnya matamu memilki hak atas dirimu, dan tubuhmu juga memiliki hak-haknya, demikian juga keluargamu memiliki hak-hak yang harus kau penuhi. Maka salat dan tidurlah, berpuasa dan berbukalah”.
Dalam ajaran moderatnya, Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau (la’ib dan lahw)[8] seingga sangat tegas mengecam:
- Sikap hidup yang lebih mengedapankan kehidupan dunia dari kehidupan ahirat padahal yang terakhir “lebih baik” dan “lebih kekal” (al-A’la:16-17);
- Orientasi hidup dengan menempatkan sukses kehidupan dunia sebagai tujuan final sehingga di akhirat “tidak memperoleh apa-apa”( al-Baqarah: 200); dan
- Kecintaan kepada harta yang berlebihan (al-Fajr:20).

Itulah ajaran-ajaran pokok Islam, sejauh yang penulis pahami, mengenai kehidupan dunia yang sangat jelas dan realistis dalam arti sesuai dengan fitrah manusia: “Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam) yang sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu…” (Ar-Rum:30). Cinta berlebihan kepada dunia jelas bukan bagian dari fitrah manusia; ia menurut Nabi Saw(*) merupakan “pangkal dari segala kesalahan”. Wallahu’alam ….@
[1] The Gospel of Ramakrishna (1907:44-45), The Vedanta Society, New York.
[2] Lihat tulisan penulis “Senam Filsafat” dalam posting sebelumnya.
[3] The Gospel, halaman 8-9.
[4] Ibid, halaman 45-46.
[5] Ibid, halaman 46-47.
[6] Al-Quran, al-Imran ayat 14, The Wisdom, Al-Mizan Publishing House, 2013.
[7] Martin Lings (Abu Bakar Siraj al-Din), Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik, Halaman 309-310, PT Serambi Ilmu Semesta, 1991
[8] Al-Hadid (20).
(*) Menurut satu sumber sabda Nabi Isa AS: Abu Nu’aim al Ashbahâny (w. 430 H), Hilyatul Awliya wa Thabaqâtul Ashfiyâ’, Juz 6 hal 338, sebagaimana dikemukakan dalam https://mtaufiknt.wordpress.com/2011/12/19/cinta-dunia-adalah- pangkal-kesalahan/