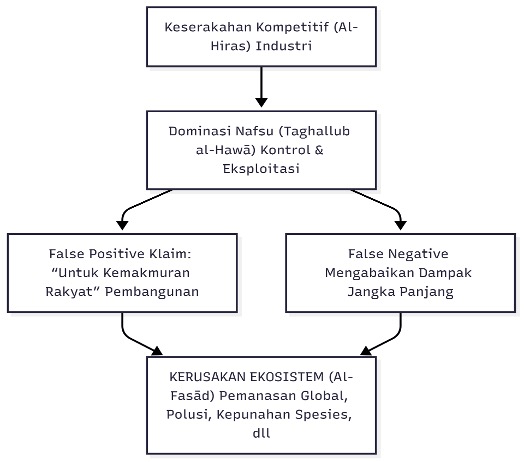Agus menatapi paras Si-kecil (6 bulan) yang tengah tidur lelap di samping putri sulungnya (3 tahun) yang juga lelap. Sore tadi Si-kecil terpapar demam yang mencemaskan. Ibunya dengan sigap membawanya ke dokter spesialis swasta yang bagi Agus bertarif terlalu mahal. Buktinya semalam ia mengeluarkan sepertiga honor bulanannya untuk sang dokter. Tetapi dalam hal dokter ini istrinya fanatik sehingga Agus hanya bisa mengurut dada. “Urusan kesehatan anak kok coba-coba”, argumen istrinya ketika Agus menyarankan untuk mencoba dokter umum atau Puskesmas. Di dua jenis pelayanan ini Agus dapat memanfaatkan BJPS Kesehatan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya berarti.
“Sudah turun panasnya”.
Agus kaget mendengar suara istrinya yang dikira masih di belakang. Tetapi dia lega melihat istri terkesan lega.
“Jam tiga tadi dia baru tidur”, lanjut istrinya.
Agus membayangkan istrinya bergadang dan mungkin juga menggendong si kecil sesekali. Ia tidak tahu persis karena lagi “pisah ranjang”. Maksudnya, akhir-akhir ini dia biasa tidur di ranjang terpisah, bahkan di kamar berbeda.
Paling tidak ada empat alasan kenapa dia pisah ranjang. Pertama, Agus sering menerima telepon malam hari soal pekerjaan kantor dari atasan langsungnya, seorang ibu separuh baya yang terkenal taft. Agus tidak keberatan karena menganggapnya sebagai risiko kerja. Kedua, dia terkadang bangun malam untuk salat sunat yang dikhawatirkan mengganggu tidur istri dan anak-anaknya. Ketiga, ranjang di kamar tidur utama terlalu sempit untuk empat kepala. Keempat, istrinya tidak keberatan.
Setelah pamit kepada istri Agus dengan tenang mengendarai motor menuju stasiun KA terdekat. “Paling menelepon ibunya”, pikir Agus ketika mengantisipasi istrinya repot karena sakitnya di-kecil. Dia merasa beruntung punya mertua yang masih cekatan, memiliki waktu bebas setelah suaminya (mantan pejabat satu BUMN) meninggal, tinggal tidak jauh dari rumahnya, dan sayang cucu. “Sayang berlebihan”, pikir Agus.
Menekan Pengeluaran
“Masih pagi”, pikir Agus ketika melihat jam dinding stasiun KA masih merujuk pada angka 5.30. Dia terbiasa memanfaatkan Commuter Line pada jam ini menuju kantornya di kawasan Jakarta Pusat. Pagi ini ia beruntung berkesempatan duduk.
Sambil menikmati duduk dengan mata terpejam-agak-kantuk ia membayangkan paras si-kecil yang tadi sempat ditatapnya. Diam-diam dia berdoa agar si-kecil dikaruniai nikmat kesehatan. Harapannya, anak-anaknya tidak perlu terlalu sering ke dokter spesialis swasta yang mahal. “Naluri protektif keibuan yang berlebihan”, bisiknya dalam hati menilai istrinya.
Bagi Agus yang bergelar S2 dan sudah berkarier sebagai PNS hampir 10 tahun membayar dokter spesialis anak identik dengan pengurangan signifikan tabungannya yang tipis. Tahun ini, tabungannya menipis drastis karena dua macam pengeluaran: (1) biaya kelahiran si-kecil, dan (2) donasi sukarela biaya kuliah keponakan yang sudah yatim sejak usia SD. Yang terakhir ini jumlahnya lumayan besar tetapi dilakukan antara lain karena dorongan istri. Dalam hal kepekaan sosial istrinya layak diacungi jempol.
Walaupun tabungannya tipis Agus masih berharap tahun depan mampu menunaikan zakat. Tahun ini, untuk pertama kali dalam 5 tahun terakhir, ia tidak berzakat karena tabungannya di akhir waktu penghitungan tidak memenuhi nisab atau batas minimal untuk berkewajiban zakat.
Jam masih menunjukkan pukul 6.35 ketika Agus turun dari kereta di stasiun terakhir dan segera menyusuri trotoar jalan kaki ke kantor yang masih dalam rentang walking distance.
Kebiasaan jalan kaki dari stasiun terakhir ke kantor sudah dimulai setahun lalu. (Kebiasaan sebelumnya ngojeg.) Bagi Agus ini bagian upayanya untuk menekan pengeluaran. Upaya lainnya termasuk beberapa jenis pengurangan frekuensi: (1) frekuensi minum jus sirsak yang merupakan hobi beratnya, (2) frekuensi mentraktir istri makan bakso, dan (3) frekuensi menikmati double espresso di Starbucks Coffee yang juga merupakan hobi beratnya.
Menyempurnakan Tugas
Ketika memasuki ruang kerjanya dan baru menyalakan komputer Agus dipanggil menghadap Bos (besar). Ia segera melapor singkat ke atasan langsungnya. Kebetulan ia berada di kantor padahal pada jam itu bisanya belum hadir karena kesibukan luar. Agus melapor ke Ibu karena tahu itulah etika dan prosedur standar kantor.
Ketika menghadap Bos dia memperoleh perintah singkat: “Ihsan, Bapak lusa akan menghadiri rapat antar-kementerian bertemakan B di Kementerian A. Kamu siapkan bahannya. Besok jam 8 sudah siap ya”. Agus merespons, “Siap Pak”. “Mohon izin bertanya Pak. Nama saya Agus, bukan Ihsan. Apa Bapak tidak salah panggil”. Bos menjawab: “Oh tidak, tidak. Yang Bapak maksud memang kamu, tadi hanya salah sebut nama. Tadi pagi Bapak baru baca artikel bagus mengenai Ihsan, jadi keceplosan memanggilmu Ihsan”.
Agus lega mendengar penjelasan Bos. Sambil menuju ruang kerjanya ia mulai membayangkan rencana kerja untuk menyelesaikan tugas barunya ini. Sebelum mulai mengerjakannya ia melapor ke Ibu yang kali ini berbaik hati memberikan arahan singkat: “Untuk keperluan Bos kamu cukup menyiapkan pointers dan catatan ringkas, jangan bertele-tele”. “Siap Bu”, respons Ahmad.
Setelah melapor Agus langsung googling mencari informasi yang relevan mengenai Kementerian A dan Tema B. Maklum dia merasa awam soal keduanya. Ia menghabiskan sekitar satu jam untuk kegiatan ini sebelum akhirnya merasa memiliki bahan cukup.
Selesai googling dia mulai menyusun pointers sesuai arahan Ibu dan menggunakan waktu 90 menit untuk menyelesaikannya. Ia segera melapor ke Ibu yang menerimanya datar-datar saja. Ibu sempat memberikan sedikit koreksi walaupun kebanyakan (seperti biasanya) trivial, tidak substantif. Ia kembali ke komputernya untuk mengakomodasikan arahan Ibu walaupun menyadari sudah kehilangan sepertiga waktu istirahatnya.
Ketika menuntaskan pointers (dalam Words) sebenarnya ia telah menyelesaikan tugasnya menurut ukuran normal kantornya. Walaupun demikian ia merasa yang dilakukannya belum sempurna dan berniat untuk menyiapkan versi Power Point setelah makan siang. Dia bermaksud mengonsultasikan dengan Ibu mengenai idenya ini tetapi yang bersangkutan sudah keluar. “Tidak akan kembali sampai besok pagi”, kata sekretarisnya.
Ia melanjutnya niatnya menyiapkan Power Point yang dilengkapi logo kantor dan aksesori sederhana tetapi apik: “Biar besok pagi dikonsultasikan dengan Ibu”, pikirnya.
Usai menyelesaikan Power Point Agus masih belum puas. (Ia terkenal kreatif dan sedikit perfectionist.) Ia dapat membayangkan dalam rapat nanti Bos memiliki peluang memberikan sumbangan pikiran substantif. Agus meyakini kantornya memiliki ladang subur untuk menanam kebaikan bagi kepentingan masyarakat luas. Keyakinan ini yang selalu menyalakan semangatnya mengabdi sepenuh hati.
Didorong oleh pikiran ini ia berpikir untuk menyiapkan artikel singkat sebagai pelengkap Power Point: “Biar besok pagi hasilnya dikonsultasikan dengan Ibu”, pikirnya. Ia mulai menggarap artikel itu walaupun tidak selancar dugaannya. Penulisan artikel ternyata perlu diselingi googling untuk memperoleh evidence-based yang kuat dan argumen yang meyakinkan untuk menghasilkan artikel kredibel. Ia menyadari Bos-nya yang menyandang gelar PhD itu akrab dengan model artikel ilmiah.
Agus menyelesaikan artikelnya satu jam setelah jam-pulang-kantor sehingga harus berdesak-ria dalam kereta. ia tidak keberatan dengan situasi tidak nyaman itu karena menyadari sudah menjadi risiko kerja. Sebelum pulang ia sempat mem-print artikelnya. Niatnya, malam nanti kan memeriksa artikel agar lebih sempurna.
Paginya dia bersyukur memeriksa artikel karena ternyata masih mengandung beberapa kekurangan. Dia berangkat kerja lebih pagi untuk menyelesaikan penyempurnaan yang ternyata hanya butuh waktu 15 menit. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini waktu menunjukkan pukul 7.30. “Masih ada waktu mengonsultasikan dengan Ibu”, pikirnya. Sayangnya yang bersangkutan belum ada di kantor. Ia menunggu sampai sekretaris menginformasikan Ibu baru siang nanti di kantor. Karena informasi ini ia menyerahkan seluruh hasil kerjanya langsung ke Bos karena sudah mendekati tenggang waktu yang diberikan.
Sabar, sabar
Setelah menyerahkan tugas ia merasa lega dan berniat untuk santai sejenak. Niatnya urung: ia dipanggil Ibu yang baru tiba dan di luar dugaan marah berat karena merasa dilangkahi: “Kenapa kamu menyerahkan hasil kerja ke Bos sebelum Aku periksa?, dst., dst., ..,,” Agus sempat terenyak dan hampir marah. Tetapi segera menyadari ia tengah berhadap dengan atasan. Amarahnya pun segera mereda: “Ya Bu”, responsnya pendek. Dengan lunglai ia kembali ke ruang kerjanya.
Di ruang kerjanya sempat terpikir oleh Agus bagaimana dirinya sering diperlakukan tidak adil oleh Ibu. Dua teman seangkatannya yang juga anak buah Ibu memperoleh promosi jabatan dua tahun lalu padahal “kinerjanya biasa-biasa saja” menurut teman sejawat. Tetapi Agus segera menyadari pikirannya itu berasal dari Setan sehingga ia segera bersistigfar. Ia merasa hampir menghujat kebijaksanaan Tuhan sehingga segera menangkan diri: “Sabar, sabar. Apa yang menjadi nasibmu adalah izin Tuhan dan ini berati yang terbaik bagimu”, bisiknya dalam hati.
Agus populer di kalangan teman-teman antara lain karena dinilai terlalu lama di posisinya sekarang. Normalnya, tiga tahun lalu ia sudah memperoleh promosi jabatan. Agus mengetahui penilaian koleganya tetapi sama-sekali tidak merasa terganggu. Ia tetap bermuka jernih ketika bekerja dan bergaul di lingkungan kantor.
Di lingkungan kantor Agus juga populer sebagai PNS yang baik: hampir tidak pernah terlambat tiba di kantor, rajin bekerja dan produktif-kreatif, selalu bermuka jernih dan tidak pernah melawan atasan.
Agus-Ahmad-Ihsan
Sebenarnya label “PNS yang baik” untuk sosok Agus terlalu sederhana. Ia mewakili sosok “PNS yang terpuji”. Label terpuji sesuai bagi Agus yang bernama lengkap Ahmad Agus: Ahmad (Arab) artinya terpuji.
Selain berlabel Ahmad, sosok Agus sebenarnya juga layak dilabeli Ihsan. Alasannya, Agus terbisa menyelesaikan tugas lebih dari yang dituntut secara formal yang menurut para ustaz merupakan ciri Ihsan. Kata ustaz Ihsan adalah “puncak kebaikan”; Ihsan tidak hanya melakukan pekerjaan secara sempurna menurut aturan, tetapi melakukannya dengan mengerahkan inteligensi (Inggris: intelligence, lebih luas dari pada mind), dan jiwa (Inggris: soul). Juga menurut ustaz, Ihsan memiliki kemampuan untuk memberikan donasi sukarela dalam keadaan sulit dan untuk menahan amarah. Semua ciri-ciri ini ada pada Agus bahkan sudah merupakan akhlak atau kebiasaan spontannya.
Demikianlah Agus, sang PNS. Dalam populasi PNS banyak Agus-agus lain yang jumlahnya cenderung meningkat. Walaupun demikian, kelompok ini tetap minoritas dan umumnya tidak berbakat untuk menarik perhatian atasan. Bagi mereka, mengasah bakat ini identik dengan mengaburkan nilai profesionalisme sejati….@