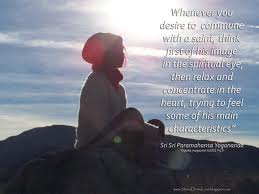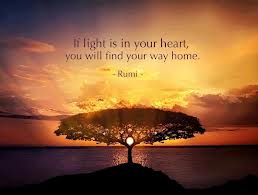Kebajikan berdimensi ganda [1]. Hal ini tercermin dari padanan katanya dalam Bahasa Inggris yaitu virtue atau dalam Bahasa Arab yaitu al-birr. Dalam kamus Bahas Inggris, kata virtue mengandung unsur integritas (integrity), adil (justice), sederhana (temperance), murni (purity), patut (decency), pantas (merit), beda (distinction), dan unggul (excellence)[2]. Dalam kamus Bahasa Arab kata al-birr mengandung unsur kejujuran (asshidieq) dan ketaatan (tha’ah), kebaikan (khair), kemasalahatan (ishlah), dan sebagainya[3].
Dari uraian singkat di atas tampak jelas bahwa semua unsur virtue maupun al-birr bernilai positif. Walaupun demikian, perbandingan yang cermat menujukkan bahwa konotasi dari dua kata itu sebenarnya tidak sepenuhnya sama: sementara yang pertama lebih banyak merujuk pada, meminjam istilah Schuon, kebajikan alamiah (natural value), yang kedua pada kebajikan supra-alamiah (supernatural value). Yang menjadi perhatian tulisan ini adalah yang kedua karena yang pertama hanya efektif jika diintegrasikan dengan yang kedua sebagaimana dinyatakan Schuon dalam kutipan berikut[4]:
Thus it is important to understand that the natural virtues have no effective value save on the condition of being integrated into the supernatural virtues….Natural virtue does not, in fact, exclude pride, that worst of illogicalities and that of preeminent vice; supernatural virtue alone –rooted in God—excludes that vice, in the eye of Heaven, cancels all the virtues. Supernatural virtue –which alone is fully human—coincide with humility; not necessarily with sentimental and individualistic humanitarianism, but with the sincere and well-grounded awareness of our nothingness before God and our relativity in relation to others. To be concrete, we would say that a humble person is ready to accept even a partially unjust criticism if it comprises grain of truth, and if it comes from a person who is, if not perfect, at least worthy of respect; a humble person is not interested in having his virtue recognized, he is interested in surpassing himself; hence in pleasing God more than men.
Adalah penting bagi kita untuk mengerti bahwa kebajikan alamiah tidak memiliki nilai efektif kecuali jika terintegrasikan ke dalam kebajikan supra-alamiah… Kebajikan alamiah tidak bebas dari kesombongan, sesuatu yang paling tidak logis dan merupakan induk dari segala keburukan; hanya kebajikan supra-alamiah –yang bersumber dari Tuhan—yang dapat terbebas dari keburukan yang dalam pandangan Langit dapat menghanguskan semua amal kebaikan. Kebajikan supra-alamiah –dan ini yang sepenuhnya manusiawi – berhimpitan dengan kebersahajaan; tidak harus sentimental atau sejalan dengan humilitiarisme individualistik, tetapi bertepatan dengan kejujuran dan kesadaran kokoh mengenai kekerdilan kita di hadapan Tuhan dan relativitas kita di hadapan yang lain. Agar kongkrit, kita dapat katakan bahwa seorang yang bersahaja siap menerima suatu kritik yang sekalipun sebagian tidak adil sejauh tetapi mengandung benih kebenaran, dan sejauh itu datang dari orang yang –jika tidak sempurna—paling tidak layak dihormati; seorang yang bersahaja tidak tertarik agar kebajikannya diakui, ia hanya tertarik untuk mengatasi dirinya; mencari lebih keridoan Tuhan dari pada pujian manusia.
Dari kutipan di atas dapat dipetik paling tidak dua macam pembelajaran yang saling terkait. Pertama, kebajikan (supra-alamiah) bebas dari kesombongan (pride) sehingga bertepatan dengan kebersahajaan (humility). Kedua, kebersahajaan ini berbasis nilai Ketuhanan (rooted in God) yaitu kejujuran (Arab: assiddieq) dan kesadaran kokoh mengenai kekerdilan diri di hadapan Tuhan dan mengenai kesetaraan atau relativitas dirinya di hadapan yang lain.
Dari kutipan di atas juga tersirat arti penting hubungan vertikal (“tali Allah”) dan hubungan horizontal (“tali manusia”) dalam konteks kebajikan; yang kedua ini merupakan basis dari kemurahan-hati (charity). Dua jenis “tali” ini perlu dipegang_teguh agar terhindar dari kehinaan (dzillah): “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanian) dengan manusia…”[5]

Varian Kebajikan[6]
Kebajikan (supra-alamiah) memungkinkan kebenaran (veracity) menjadi kongkrit, terlihat dan hidup: tanpa unsur kebajikan, kebenaran tidak tampak atau seolah-olah tidak bertubuh (imposture). Di sisi lain, dalam perspektif spiritual, kebajikan menjadi tidak bermakna jika tidak dilandasi kebenaran.
Uraian di atas juga menyinggung kaitan kebijakan dengan kebersahajaan dan kemurahan-hati, dua wujud dari kebajikan fundamental (fundamental value). Agar berkah atau manjur, masing-masing kebijakan fundamental itu perlu dipadukan sehingga menghasilkan dua varian kebajikan: (1) “kebersahajaan” bersifat “murah hati” (charitable humility) dan (2) “murah-hati” bersifat “bersahaja” (humble charity).
Karena merupakan wujud kebajikan, masing-masing kebajikan fundamental itu, agar bermakna, membutuhkan kebenaran sebagai landasan. Kombinasi kebenaran dengan kebersahajaan menurunkan dua varian kebajikan: (3) kebenaran yang bersahaja (humble veracity) dan (4) kebersahajaan yang benar (truthful humility). Pada sisi lain, kombinasi kebenaran dengan kemuahan_hati menurunkan varian kebajikan: (5) kebenaran yang murah hati (cahritable veracity) dan (6) kemurahan hati yang benar (truthful charity).
Hemat penulis, memahami 6 (enam) varian kebajikan penting selain untuk memperkaya pemahaman kita mengenai kebajikan tetapi, tetapi juga agar tidak terjebak dalam semangat atau kecenderungan untuk memberikan penekanan yang berlebihan yang tidak perlu (overemphasis) terhadap suatu kebajikan fundamental tertentu.
- “Kebenaran yang murah hati” (varian ke-5), sebagai contoh, mengingatkan kita bahwa kebenaran bukan hanya untuk keperluan diri-sendiri tetapi perlu di-share dengan orang lain, tentunya dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dipahami.
- “Kebersahajaan yang benar” (varian ke-4) dan “kemurah-hatian yang benar” (varian ke-6), sebagai contoh lain, menegaskan bahwa “kebersahajaan” dan “kemurah-hatian” harus sesuai dan mengungkapkan kebenaran, bukan bertentangan dengannya.
Contoh terakhir ini mengilustrasikan betapa tidak eloknya melakukan suatu aksi atas nama “kebenaran” tetapi mengabaikan “kebersahajaan” dan “kemurahan_hati” ketika melakukan aksi itu. Wallaahu’alam.
Teks Suci Mengenai Kebajikan
Kebajikan bersifat universal dalam arti dapat ditelusuri dalam teks suci semua agama atau tradisi besar manusia sepanjang sejarah. Dalam konteks Islam, narasi megenai kebajikan (al-birr) dalam berbagai kontkes antara lain dapat ditemkan dalam ayat-ayat al-Qur’an berikut:
- Ayat (3,92): Kebajikan tidak dapat kita diraih kecuali jika kita mampu menafkahkan sebagian harta yang kita cintai;
- Ayat (3:193): Doa agar digolongkan ke dalam golongan ahli kebajikan (al-abraar); dan
- Ayat (2:44): Kecaman kepada Bani Israil yang menyuruh orang lain melakukan melakukan kebaikan tetapi mereka sendiri tidak melakukannya.
Versi ayat yang agak panjang mengenai kebajikan dapat ditemukan dalam Ayat (2:177):
Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, kitab-kitan, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicinatinya kepada kerabat, anak yaitim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menempati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka adalah orang-orang yang benar dan mereka iulah orang yang bertakwa[7].
Ayat itu menyebut ahli kebajikan sebagai orang-orang yang benar atau jujur (shodaquu) dan bertaqwa (muttaquun). Ayat itu mungkin paling lengkap dalam menggambarkan kebajikan karena mengandung unsur ketiga pilar Agama Islam (sesuai “hadits Jibril”) yaitu Iman, Islam dan Ihsan:
- Unsur Iman: percaya kepada Allah dan rukun iman lainnya,
- Unsur Islam: melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan
- Unsur Ihsan: memberikan harta yang dicintai kepada yang berhak, menempati janji, sabar dalam penderitaan.
Wallahu’alam bimuraadih….@
[1] Dalam situs ini dapat diakses tiga tulisan serupa dengan tulisan ini tapi lebih sederhana: (1) Rendah Hati (1/1/16), Kebajikan Fundamental (24/4/12) dan Kebenaran dan Kebajikan (21/4/12).
[2] Lihat misalnya, Webster’s Pocket Thesaurus, New Revised Edition (2002)..
[3] Lihat , misalnya, Kamus Lisaânul ‘Arabî.
[4] Frihjof Schuon (1988:51-52), To Have A Center, World Wisdom Books.
[5] Al-Imran 112; terjemahan dikutip dari The Wisdom: Al-Qur’an Disertai Tafsir yang Memudahkan Siapa Saja untuk Memahami Al-Qur’an, 2014, PT Mizan Bunaya Kreativita.
[6] Disarikan dari Shuon, “Spiritual Perspectives and Human Facts”, World Wisdom online library: http://www.wordpresss.com/public/library/ default.aspx
[7] Dikutip dari The Wisdom: Al-Qur’an Disertai Tafsir yang Memudahkan Siapa Saja untuk Memahami Al-Qur’an, 2014, PT Mizan Bunaya Kreativita